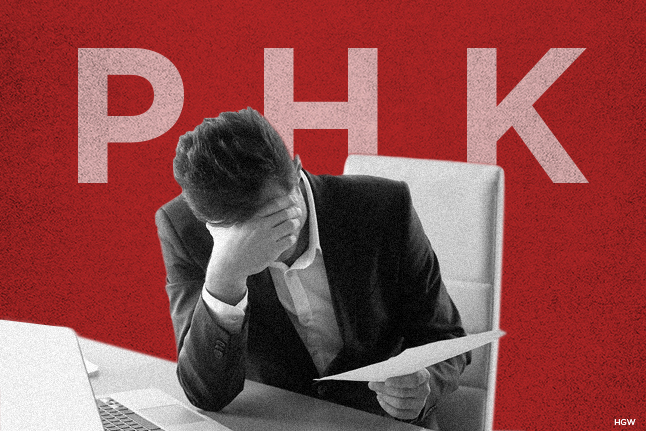
Ilustrasi Polemik Gelombang PHK Sumber: Hukumonline.com
Hingga 23 April 2025, Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker) mencatat sedikitnya 24.036 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Tiga sektor paling terdampak ialah industri pengolahan (16.801 orang), perdagangan besar dan eceran (3.622 orang), serta aktivitas jasa lainnya (2.012 orang). Angka ini mencapai hampir sepertiga dari total PHK sepanjang tahun 2024 (77.965 orang) dan bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 (64.855 orang) serta 2022 (25.114 orang).
Menaker Yasasierli, menyebut kerugian perusahaan, penutupan usaha, dan perselisihan hubungan industrial sebagai pemicu utama PHK. Namun belakangan, gelombang PHK juga menyentuh sektor lain seperti wisata dan perhotelan, hingga industry media —termasuk ANTV, iNews, dan Kompas TV.
“Menurut saya ada kebijakan efisiensi pemerintah yang tanpa disadari berdampak pada honorer dan pekerja kontrak. Dana pemerintah berkurang, mereka kehilangan proyek, dan akhirnya terjadi PHK di sektor swasta,” ujar Tadjuddin Noer Effendi, Guru Besar FISIP Universitas Gadjah Mada. Ia menambahkan, melemahnya daya beli masyarakat dan kebijakan impor yang longgar semakin memukul pabrik-pabrik lokal. Efek domino inilah yang memicu PHK massal di berbagai lini industri.Kemenaker mencatat tujuh alasan utama PHK, salah satunya adalah tindakan balasan pengusaha terhadap aksi mogok kerja (union busting)—yang secara tegas dilarang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam pasal terkait, mogok kerja adalah hak dasar pekerja, dan pengusaha dilarang memberi sanksi.
Pergolakan yang dilakukan oleh para pekerja ini merupakan manifestasi dari perjuangan kelas melawan spirit kapitalisme yang mengakar dalam sistem ekonomi dimana kapitalisme meniscayakan segalanya demi keuntungan dan kepentingan tertentu seperti eksploitasi terhadap buruh. Berdasarkan teori konflik Karl Marx, gerakan Serikat Pekerja ini merupakan bagian dari perjuangan kelas proletar untuk melawan dominasi kelas borjuis. Adanya aksi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja ini merupakan upaya yang dilakukan oleh kaum proletar untuk memperoleh upah yang setara, jaminan akan keselamatan kerja, serta keadilan.
Tingginya gelombang PHK massal ini membuat ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian mereka. Kondisi ini kemudian memperparah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, diantara penyebab kemiskinan di Indonesia adalah kapitalisasi dalam sistem pendidikan, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, serta keterbatasan lapangan pekerjaan dan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Potret kemiskinan di Indonesia tercermin dari kondisi masyarakat yang tidak merasakan kesejahteraan untuk memenuhi hajat hidup mereka seperti tempat tinggal yang layak, akses terhadap air bersih, makanan bergizi, kesempatan menempuh pendidikan tinggi, serta rendahnya akses layanan kesehatan. Ironinya, Bank Dunia mengungkap persentase penduduk miskin di Indonesia sebagai yang tertinggi nomor empat di dunia dari kelompok negara berpendapatan menengah ke atas pada 2024, yaitu mencapai 60,3 persen.
Menurut Laporan Prospek Ekonomi Global Bank Dunia 2024, persentase penduduk miskin Indonesia tergolong tertinggi ke-4 di antara negara berpendapatan menengah ke atas, mencapai 60,3 %. Ironisnya, meski berbagai program bantuan berjalan, masih banyak rumah tangga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar—dari tempat tinggal hingga akses air bersih. Kondisi kemiskinan yang semakin parah ini menegaskan satu hal: ketidakhadiran dan abainya negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Baik dalam penyediaan lapangan kerja maupun penyaluran bantuan sosial, masih banyak yang perlu dibenahi agar stabilitas ekonomi dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi kemiskinan yang masih terjadi hingga hari ini bukanlah hal yang remeh dan merupakan persoalan serius yang harus segera di tuntaskan.
Penulis: ONF
